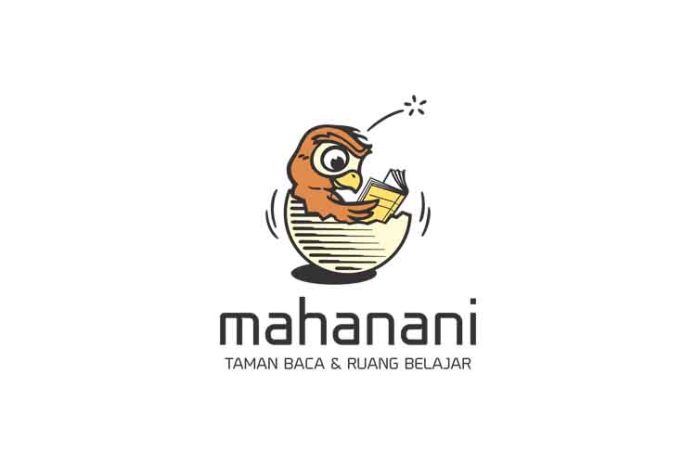Sebuah Maklumat: Sebelum ke Maklumat Sastra Profetik-nya Kuntowijoyo
Bulan puasa bagi banyak orang merupakan bulan yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya dalam satu tahun. Begitu pun bagi saya pribadi. Pada bulan puasa ini—saat ini tahun 2025 M atau 1446 H—saya melakoni suluk rutinan saban Ramadhan. Suluk itu ialah ngabubookread. Membaca sambil menanti waktu berbuka puasa. Namun tidak membaca karya-karya non-fiksi. Melainkan membaca karya-karya sastra, baik novel, puisi, atau kumpulan cerpen.
Perjalanan membaca saya tahun ini mengantarkan saya pada seorang “begawan” dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sejarah, yakni Kuntowijoyo. Nama ini sebenarnya sudah sejak lama saya dengar. Pada pertengahan 2020 saya pernah direkomendasikan sebuah novel berjudul “Khotbah di Atas Bukit” karya Kuntowijoyo oleh salah seorang kawan saya, Yophie, dari jurusan Sejarah.
Setelah membaca novel itu, saya mengetahui bahwa Kuntowijoyo ialah seorang sastrawan keren—belum menyadari bahwa ia adalah seorang yang diluhurkan dalam ilmu sejarah. Mengapa saya menyebut sebagai sastrawan keren? Sebab dalam novel yang ia tulis itu sungguh-sungguh terasa aura sufistiknya. Apalagi ada satu kutipan dari novel tersebut yang saya ingat betul sampai hari ini: “Hidup ini tak berharga untuk dilanjutkan. Bunuhlah dirimu!” Sungguh magis bagi saya pribadi.
Seiring berjalannya waktu, saya pun sampai pada sebuah maklumat sastra dari Pak Tua yang saleh ini: Maklumat Sastra Profetik (Selanjutnya saya tulis MSP).
Maklumat ini saya buat sebagai bentuk hormat saya atas Kuntowijoyo yang telah dengan baik hati menuliskan Maklumat Sastra Profetik. Betapa tidak, tiap membaca karyanya, entah novel atau cerpen, selalu ada hal-hal yang bernada transenden. Sangat spirituil, namun dekat dengan keseharian. Andai saja Kuntowijoyo tak pernah menuliskan MSP, mungkin saja saya akan sering dihantui pertanyaan,”sebenarnya sastra jenis apa yang ditulis oleh Begawan Sejarah satu ini?”
Jadi, apa sebenarnya Sastra Profetik itu?
Bagi Kuntowijoyo, sastra profetik merupakan “sastra ibadah” yang mengekspresikan penghayatan nilai-nilai agama yang dianutnya serta sastra murni yang merupakan ekspresi dari tangkapannya atas realitas. Bahkan ia menegaskan bahwa sastra merupakan caranya untuk mengabdi pada Tuhan dan tanah air.
Kuntowijoyo dalam MSP ini terilhami oleh ayat suci Al-Quran dalam Surat Ali Imran ayat 110. Singkatnya dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa nilai-nilai kenabian ada tiga hal, yaitu ‘amar ma’ruf, nahi mungkar, dan, tu’minu billah. Ketiga hal tersebut yang nantinya akan menjadi etika profetik, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi.
Menariknya lagi, inspirasi sastra profetik ini salah satunya didapat Kuntowijoyo dari Muhammad Iqbal, seorang filsuf muslim yang masyhur. Dari Muhammad Iqbal, Kuntowijoyo menginsyafi bahwa fenomena Isra’ Mi’raj itu luar biasa hikmahnya—sekaligus kritik terhadap kaum sufi yang acapkali memilih menjauh terhadap kehidupan dunia. Dalam fenomena Mi’raj, Nabi Muhammad Saw telah mencapai puncak dan bertemu Tuhan. Suatu capaian yang diidam-idamkan oleh para praktisi tasawuf.
Namun setelah menemui Tuhan, Nabi justru turun ke bumi dan melaksanakan tugas kerasulannya; membina umat, mengajak pada kebaikan, dan menjadi rahmat bagi sekalian alam.
Kaidah Sastra Profetik
Dalam hal ini Kuntowijoyo membagi kaidahnya menjadi tiga bagian. Akan saya uraikan secara singkat apa saja kaidah dari sastra profetik tersebut.
Kaidah Pertama, Epistemologi Strukturalisme Transendental. Mendengar tiga kata itu kesan yang saya tangkap pertama ialah berat. Serba ndakik-ndakik. Ternyata tidak. Dalam kaidah epistemologi strukturalisme transendental ini secara singkat Kuntowijoyo ingin mengatakan bahwa sastra berdasar pada kitab suci. Bagaimana seorang pengarang dapat mengkaji kitab suci, lalu mendedah-resapi saripati & nilai-nilai dari kitab suci itu terhadap karya sastra yang dikarangnya.
Kaidah Kedua, Sastra sebagai Ibadah. Dalam kaidah ini Kuntowijoyo dengan tegas menuliskan bahwa, “Pengarang yang salat dengan rajin, zakat dengan ajeg, haji dengan uang halal, Islamnya tidaklah kaffah kalau pekerjaan sastranya tidak diniatkan ibadah.” (hlm 4). Bagi saya kaidah ini memiliki jalin kelindan dengan kaidah pertama.
Jika telah mendapat ilham dari kitab suci, maka seorang pengarang harus melaksanakan tugasnya sebagai pengarang, yaitu menuliskan sesuatu yang berdasarkan nilai-nilai dari kitab suci. Lalu melaksanakan tugas dari Tuhan sebagai manusia supaya bekerja untuk manusia pula. Hal ini kemudian yang mengantarkan kita untuk mengorek kaidah selanjutnya.
Kaidah Ketiga, Keterkaitan Kesadaran. Kesadaran di sini yang dimaksudkan harus saling berkaitan satu sama lain. Hal tersebut ialah kesadaran ketuhanan dan kesadaran kemanusiaan. Dalam kaidah ini Kuntowijoyo juga menegaskan bahwa tugas kemanusiaan sastra profetik yaitu memperluas ruang batin, serta menggugah kesadaran ketuhanan dan kesadaran kemanusiaan.
Lalu dalam menulis sastra, Kuntowijoyo selalu berpegang pada tiga unsur, yaitu pengalaman, imajinasi, dan nilai. Kendati demikian, tak jarang pula ia menulis sastra dengan hanya dua nilai; baik antara pengalaman & imajinasi, atau nilai & imajinasi.
Perlu kita ketahui pula bahwa semua karya sastra Kuntowijoyo, tuturnya dalam MSP, adalah transendensi. Kuntowijoyo menulis karena baginya hidup adalah misteri yang mengagumkan. Oleh karena itu, seorang pengarang memiliki kewajiban ganda. Sebagai manusia ia harus menjadi saksi eksistensi Tuhan. Sedangkan sebagai pengarang, ia harus menjadi saksi rahasia Tuhan. Maksudnya ialah pengarang merupakan saksi kreatif-imajiner misteri kehidupan manusia ciptaan-Nya.
Sedikit berat memang jika dipikir-pikir menjadi pengarang itu. Tapi gagasan demikian cukup menarik, apalagi dalam zaman seperti ini. Zaman keberlimpahan informasi, budaya yang serba viral, bahkan kedaulatan selera kita yang kini didikte algoritma. Semuanya tak ayal dapat menyebabkan kita menjumpai krisis—yang dalam MSP disebut dengan krisis peradaban. Krisis karena manusia-manusia mulai retak dengan makna hidupnya, dengan kedalaman batinnya.
Krisis tersebut mustahil jika hanya diselesaikan dengan politik—sekali pun politik itu baik, apalagi politik yang jelek. Butuh banyak hal yang saling bahu-membahu untuk menanggulangi krisis tersebut. Dalam hal ini sudah menjadi tugas sastrawan yang sangat relevan dan efektif untuk mengobati krisis tersebut dengan mengembangkan makna hidup pada kemanusiaan.
Agaknya demikianlah maklumat ini saya buat. Dalam bulan yang suci, maklumat ini saya buat sebagai sebentuk dzikir, pengingat, bahwa sastra itu juga sebuah ibadah; bahwa kerja-kerja kepenulisan, kepengarangan, tak ada yang sia-sia; bahwa kita pernah memiliki seorang sastrawan saleh yang rendah hati, yakni Kuntowijoyo.