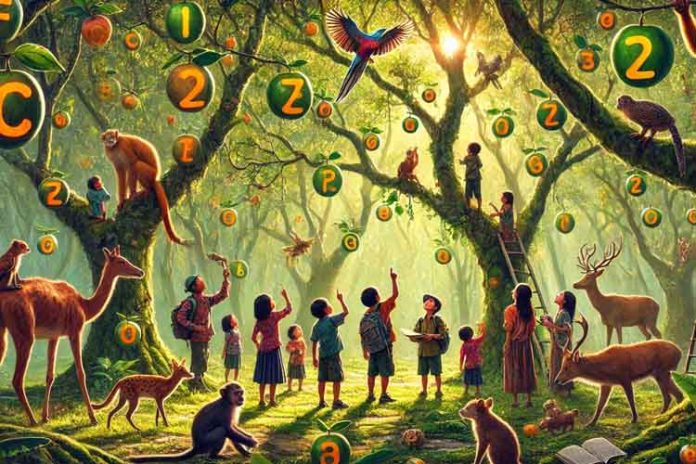Saat mempersiapkan materi diskusi bedah Buku Indonesia Bagian Dari Desa Saya, saya menerima kiriman kartu kredit dari Bank Mandiri. Setelah beberapa hari sebelumnya saya menerima telepon dari CS Bank Mandiri untuk meminta konfirmasi apakah saya bersedia untuk dikirimi kartu kredit. Saya iyakan saja penawaran dari seberang telepon. Saat itu saya merasa biasa ketika menerima tawaran fasilitas kartu kredit dari Bank Mandiri. Sayapun menjawab iya sebenarnya untuk mempersingkat percakapan dengan CS Bank Mandiri. Sampai kemudian, selang beberapa hari kiriman kartu kredit itu datang. Saya membukanya bersama anak perempuan pertama. Saya memintanya untuk unboxing, menyobek amplop dan mengeluarkan isinya. Kartu kredit itu bertuliskan nama saya, kartu kredit platinum. Sejenak saya merasakan kebanggaan ketika mengamatinya. Saya merasa menjadi bagian dari kemajuan zaman. Saya merasa lebih keren, merasa sebagai sobat tekno.
Untung saja perasaan itu bertahan sebentar saja. Kemudian saya menyadari bahwa apa yg saya rasakan itu tepat digambarkan oleh Emha dalam bukunya Indonesia Bagian Dari Desa Saya ketika menceritakan ironi Pak K yang merasa keren dan maju dengan memiliki Honda CB 125. Ironi itu tergambar dari kondisi rumah Pak K yang terbuat dari gedek, berlantai tanah seluas 3×4 meter. Namun Pak K tidak merasakan itu sebagai keganjilan, ia justru merasa nyaman dan bangga dengan impian yang kini dikenyamnya. Bagi Pak K motor pertama-tama tidak berfungsi sebagai yang semula dimaksudkan oleh teknologi itu, melainkan sebagai indikator gengi, martabat sosial, dan bagian dari kemajuan.
Ironi itulah yang juga hadir di dalam kebanggaan saya ketika menerima fasilitas kartu kredit. Saya merasa menjadi bagian dari kemajuan dengan memiliki kartu kredit. Saya terjebak kepada konsumsi tanda yang dangkal. Menilai semata-mata mengkonsumsi apa saja yang datang dari “kota”, apa saja yang dihasilkan oleh teknologi terkini itu sebagai prestasi dan kemajuan. Dalam hal ini Pak K dan saya adalah contoh ironi. Contoh yang mengharuskan kita lebih berhati-hati menerjemahkan makna kemajuan.
Kenapa kisah di atas penting saya ceritakan untuk mengawali diskusi kita soal desa. Sebab dalam banyak diskursus desa banyak disalahpahami sebagai kejumudan (ketertinggalan) dan kota sebagai kemajuan. Dan hal-hal itu kalau kita perhatikan dengan lebih teliti kemajuan yang dimaksud adalah seberapa banyak kita mengkonsumsi produk-produk industri. Semakin kita mengkonsumsi semakin kita merasa diri bagian dari kemajuan.
Motor CB dalam cerita Pak K dan kartu kredit dalam pengalaman saya bisa diganti dengan barang-barang lainnya. Mobil, jam tangan, handphone, tas, sepatu, hewan peliharaan, maupun property. Kita tidak bisa secara sederhana dan naif barang-barang itu di dalam dirinya sendiri tidak mengandung persoalan. Motor CBnya Pak K tidaklah hadir serempak dengan taraf konsumsi/kebutuhan riilnya. Barang-barang itu justru kerap kali mencampakkan orang-orang desa sedemikian rupa ke dalam impian kemewahan yang meminta hampir seluruh hidupnya.
“Yo ngene iki jenenge urip rek”, kata Pak K sambil memarkir masuk motornya ke dalam rumah. “Wes sak mestine”, kata Pak K dan orang-orang sedesanya. Sudah selayaknya setiap orang berhak mengusahakan hidup lebih.
Sebagai patokan nilai hidup, kelayakan adalah mutlak, namun di manakah ia berada? Di manakah letaknya? Kesadaran bahwa kadar dan takaran kelayakan itu bergeser, berubah, dan terus menerus berkembang. Statisnya kelayakan juga merupakan ortodoksi yang tak dikehendaki yang bisa diartikan kemandegan. Namun kelayakan taraf hidup yang selalu diupayakan terus ditingkatkan pertama-tama tidak ditulangpunggungi oleh kesadaran dan komitmen terhadap kreativitas dan produktivitas hidup, namun lebih oleh keserakahan konsumerisme. Semua orang di desa Pak K tak lain mengejar kelayakan semacam itu. Kelayakan utamanya tidak diperangkati oleh tanda-tanda material, tetapi oleh kepekaan manusiawi terhadap batas kewajaran kebutuhan hidup kemanusiaannya. Ini bukan suatu sikap yang berusaha menceraikan barang-barang dari manusia. Keduanya bersifat komplementer dan dialektik. Pertanyaan pentingnya siapa memimpin apa atau apa memimpin siapa? Mana subjek, mana objek itulah kemajuan yang seharusnya dituju.
Diskursus tentang kemajuan kerap kali muncul dari pusat menyebar ke pinggiran, dari kota menyebar ke desa. Jarang terjadi arus yang sebaliknya. Identitas sebagai manusia yang maju, menjadi bagian dari masyarakat modern tumbuh seiring dengan meningkatnya konsumsi terhadap barang-barang “kota”. Pengejaran identitas sebagai manusia maju dan modern ini kerap kali membuat masyarakat desa tanpa sadar melepaskan nilai-nilai hidup yang lebih prinsipil dalam kehidupan bersama. Nilai kesetiakawanan, bebrayan, gotong-royong beralih rupa menjadi etos persaingan, kompetisi, keunggulan. Ini merupakan konsekuensi logis dari konsumsi barang-barang yang membutuhkan sumber daya material yang tidak sedikit untuk mendapatkannya. Dan sumber daya material itu harus dicari, didapat melalui kompetisi dan “kerja keras” untuk menjadi yang unggul di pasar.
Mengatakan di desa tidak terjadi intrik persaingan, hanya terjadi harmoni bebrayan ialah sesuatu yang absurd. Desa-kota tidak selalu dalam hubungan biner. Ada saling kelindan diantara keduanya. Seperti ditulis Emha, “terasa ada yang terurai, ada yang meluntur, mencair, semacam tak kental lagi”.
Namun dibandingkan kehidupan kota, tingkat persaingan untuk bertahan hidup relatif lebih rendah. Keberadaan kota yang ditandai dengan bermunculannya tempat-tempat transaksional untuk memenuhi hampir setiap kebutuhan, seperti supermarket, mall, bioskop, tempat karaoke, lapangan sepak bola atau futsal. Sedang di desa relatif kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi tanpa harus selalu melalui mekanisme transaksional. Kota adalah pertumbuhan dari pasar alam, pasar tradisional, di perempatan jalan menjadi pasar inpres yang bergedong bangunannya, menjadi modern shoping center lalu menjadi toko-toko spesialis. Kota adalah peralihan dari paguyuban komunitas tradisional menjadi tatanan baru yang berbidang, berkotak-kotak, deparmental. Kota dalam arti yang lebih esensial adalah perwujudan suatu jaringan sosial kehidupan tertentu yang untuk mengenyamnya diperlukan sarana dan fasilitas yang belum tentu bisa dimiliki oleh orang kota sendiri. Kota lebih dekat ke dinamika ekslusivisme dan elitisme. Kebudayaan dan pembangunan mengarah ke konsumsi teknologi modern. Pusaran tengah dari kerangka baru tersebut ialah lingkaran dinding elitisme ekonomi dan syarat involvement-nya adalah daya beli, kemampuan modal. hal 51-53).
Desa bagi Emha dalam buku Indonesia Bagian Dari Desa Saya tidak sekedar merujuk pada titik geospasial, letak geografis suatu wilayah namun juga merupakan suatu ruang hidup yang terkandung kebijaksanaan hidup yang berharga. Bagi Emha, desa sebagai fenomena kultur setidaknya lebih “murni” atau lebih “diri kita sendiri”. Desa baginya ialah akar. Desa merupakan kenyataan terbesar dari Indonesia yang menghampar di ribuan pulau ini, namun dari aspek kultur, nilai, dan manusianya, desa sedemikian marjinal. Meskipun relatif bahwa desa lebih mengaribkan kita dengan pada alam, pada sesuatu yang Emha sebut fitrah.
Kefitrahan, kealamian, dan barangkali keluguan karakter desa yang dimaksud Emha secara ekstrem digambarkan oleh karakter Pak Cendol, Yu Reso, Pak Wongso dan Bu Wongso. Karakter-karakter itu digambarkan Emha sebagai pribadi yang tidak ditaklukkan oleh kemudahan-kemudahan memperoleh uang. Mereka tetap punya darma kepada sesama manusia sebagai penjual kepada pembeli-pembelinya.
Dalam pandangan manusia maju, modern terlihatlah betapa bodoh itu Pak Cendol, Yu Reso, Pak Wongso dan Bu Wongso. Mereka tidak realistis, sok moralis, kenes bahkan sok arif. Dagang adalah dagang. Kehidupan adalah keuntungan. Kemajuan ialah merebut peruntungan. Gobloklah siapapun yang menolak keuntungan. Bahkan keuntungan, keuntungan material tentu saja haruslah menjadi satu-satunya substansi dalam hidup ini kalau bisa. Cita-cita harus untuk sukses. Sukses harus dibeli dengan ongkos apapun. Apapun profesimu, apapun bidang kerjamu, di manapun tempat tinggalmu, yang terpenting capailah sukses.
Pak Cendol, Yu Reso, Pak dan Bu Wongso tak tahu itu semua. Mereka hanya orang yang setia pada orang-orang lain. Pada para pembeli yang merupakan bagian yang erat dari komunitasnya. Mereka hanya manusia yang menjalankan — tanpa pengertian rasional-intelektual — naluri kemanusiaannya untuk memelihara keutuhan, keseimbangan, keadilan, dan kebersamaan. Mereka berdagang, tetapi bukan dagang itu sendiri esensi perbuatannya. Dagang hanya satu jalan, satu jalur, satu lorong menuju titik yang lebih inti dari proses manusianya. Mereka sendiri pastilah tidak menyadari perumusan semacam ini. Mereka hanya mengalami, hanya hidup melakoni secara alam saja.
Pak Cendol, Yu Reso, Pak dan Bu Wongso tak tahu itu semua. Mereka hanya orang yang setia pada orang-orang lain. Pada para pembeli yang merupakan bagian yang erat dari komunitasnya. Mereka hanya manusia yang menjalankan — tanpa pengertian rasional-intelektual — naluri kemanusiaannya untuk memelihara keutuhan, keseimbangan, keadilan, dan kebersamaan. Mereka berdagang, tetapi bukan dagang itu sendiri esensi perbuatannya. Dagang hanya satu jalan, satu jalur, satu lorong menuju titik yang lebih inti dari proses manusianya. Mereka sendiri pastilah tidak menyadari perumusan semacam ini. Mereka hanya mengalami, hanya hidup melakoni secara alam saja. Mereka tidak berdagang untuk berdagang itu sendiri, melainkan seperti meneguhkan kembali sesuatu yang lebih dalam, lebih inti, dan lebih murni dalam jiwa manusia mereka. Mungkin falsafah nilai, mungkin sikap hidup, mungkin kekariban bersama. Berdagang bagi mereka semacam latihan memelihara keyakinan, meneguhkan kembali, menyatakan sumpah secara diam-diam dalam batin jiwa, segala komitmen kemanusiaan mereka.
Sikap-sikap semacam itu tentu saja suatu contoh ekstrem untuk menggambarkan karakter ke-ndeso-an yang oleh mripat ke-kota-an dianggap sebagai tak praktis, jumud, mandeg, tidak menguntungkan. Tidak mengantarkan pelakunya pada puncak-puncak kesuksesan. Pak Cendol, Yu Reso, Bu dan Pak Wongso barangkali relatif mudah kita temukan di desa-desa daripada di kota-kota besar.
Lutvi Zanwar Kurniawan
Taman Baca Mahanani, 15 Juni 2024