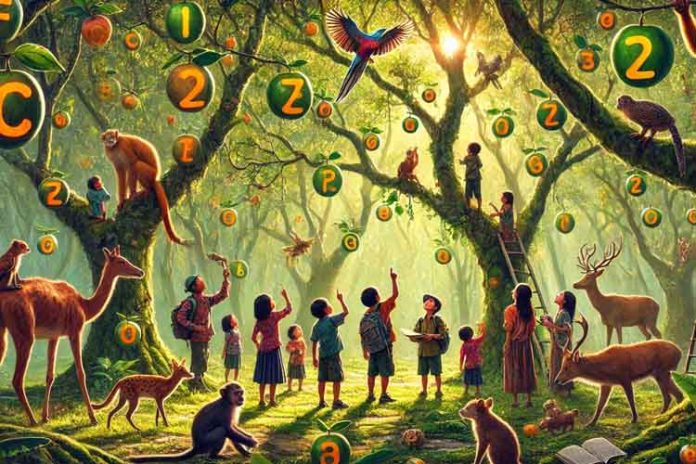Tersebutlah seorang manusia berbadan melar dengan pipi tembam dan perut yang selalu tampak bersitegang dengan pakaian. Langkahnya berat, lemas, sering tersengal meski hanya berjalan ke kulkas. Ia sering mengeluh sakit di berbagai bagian tubuh—kadang sendi, kadang perut, kadang hati saat melihat tim sepak bolanya kalah lagi—tapi tetap semangat kalau urusan makan. Sambil mengunyah ayam goreng dengan ekspresi penuh penghayatan, ia berkata dengan nada bertanya, “Aduh, kenapa sih aku kok malas sekali makan, heran deh,” lalu, dengan refleks nyaris fantastis, meraih gorengan yang hampir diambil orang lain.
Orang lain itu adalah kamu, bayangkan begitu. Maka, apa reaksimu?
Bebas mau apa, asal tidak mengabsen nama-nama binatang dan kawan-kawannya, tidak boleh melanggar adat ketimuran, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila serta Undang-undang Dasar. Kayaknya kamu akan menyindir dengan kata-kata dalam nada bertanya, “Aduh, kenapa sih kamu kok malas sekali makan, heran deh.” Tapi dalam hati kamu mulai mengabsen nama-nama binatang dan kawan-kawan, melanggar adat ketimuran, dan bertentangan dengan Pancasila serta Undang-undang Dasar.
Tenang, rasa jengkelmu itu wajar dan kamu tidak sendirian.
Plot twist-nya, rasa jengkel yang sama juga layak kamu terapkan ke orang yang bilang, “Aku malas membaca,” padahal tiap hari matanya gak lepas dari layar. Membaca chat tanpa putus, scrolling caption panjang, melahap drama di media sosial, ngepoin gosip di komentar, bahkan betah menyimak debat panas sampai ratusan balasan.
Dia gak malas membaca. Dia cuma baca yang dia suka dan dia baca buuanyak!
Apa bedanya dengan orang yang katanya “malas makan,” tapi tangannya terampil nyamber gorengan? Bedanya mungkin, orang “malas makan” (tapi segala junk-food ditelan gak ada takaran) akhirnya sakit-sakitan, sedangkan yang “malas membaca” (tapi segala junk-feed dipanteng semua) akhirnya gila-gilaan. Kalau pola makannya buruk, yang kena badan. Kalau pola bacanya sembarangan, yang kena pikiran.
Membaca atau Mati
Lagi pula, orang mengaku malas membaca, emang bisa ya?
Begitu mata melek dari tidur, otak kita langsung dihantam arus kejadian yang mustahil dihindari dan itu semua adalah “teks” yang harus kita baca meski mungkin tak secara sadar.
Di rumah, suara ibu yang mengomel soal cucian yang belum diangkat itu ibarat headline pagi yang terus muncul tiap hari. Di jalan, klakson motor, antrean kendaraan, dan ekspresi wajah orang-orang adalah paragraf-paragraf yang perlu kamu pahami kalau tak mau tersandung masalah. Di warung, obrolan tetangga tentang harga beras, gosip artis, dan politik lokal adalah berita yang tetap masuk ke kepalamu meski kamu tak berniat mengikuti.
Kehidupan ini punya tata bahasanya sendiri—tanda baca yang harus diperhatikan, subteks yang harus ditangkap, dan paragraf-paragraf realita yang harus dipahami. Orang boleh bilang malas membaca, tapi nyatanya, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, kita terus-menerus dipaksa membaca dunia.
NKRI harga mati masih bisa dikadali para pengkhianat bangsa, tapi ‘membaca harga mati’ benar-benar tak ada ampun. Kita harus benar-benar mati untuk bisa berhenti membaca.
Literasi Dog’s shit
Literasi itu sesungguhnya bukan soal bisa atau tidak bisa membaca.
Bayangkan ada orang pintar mulia hatinya datang suka rela ke sebuah desa pedalaman, ingin mengenalkan literasi ke anak-anak yang belum pernah menyentuh buku. Keliru kalau orang itu menganggap anak-anak pedalaman yang buta huruf “tidak bisa membaca.” Keliru besar yang implikasinya sebaiknya minggat saja orang itu dari sana karena tai asu lah dengan segala kepintarannya karena hanya akan memperburuk nasib mereka.
Anak-anak pedalaman—seperti halanya semua anak di dunia—bisa membaca, bahkan mungkin lebih canggih daripada kita. Hanya saja, bacaan anak-anak pedalaman bukan huruf di atas kertas, tapi tanda-tanda alam, pola kehidupan, dan bahasa yang diwariskan turun-temurun.
Kalau langit mendung, mereka tahu hujan akan segera turun, bukan karena melihat prakiraan cuaca, tapi dari perubahan arah angin dan suara serangga yang tiba-tiba lebih nyaring. Kalau melihat jejak di tanah, mereka bisa tahu hewan apa yang lewat, seberapa besar, dan seberapa lama jejak itu ditinggalkan. Mereka membaca sungai dari warna airnya, membaca hutan dari aroma dan suara, membaca wajah orang tua dari guratan di dahi.
Mengenalkan literasi bukan berarti menjejalkan huruf dan angka ke kepala mereka. Yang utama adalah meningkatkan nalar kritisnya—bertanya, menggali pemahaman mereka, mengajak mereka berpikir lebih jauh dari sekadar kebiasaan. Baru setelah itu, sambil bermain, sambil bercerita, bolehlah huruf dan angka bisa diperkenalkan sebagai alat bantu, bukan sebagai tujuan utama.
Mengenalkan literasi harus dengan anggapan dasar bahwa kita semua sudah punya kemampuan baca—tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Berkembang dalam arti menjadi meningkat taraf hidup mereka.
Apa yang terjadi pada anak-anak pedalaman sebenarnya terjadi juga di sekitar kita, hanya dalam bentuk yang berbeda. Lihat saja anak-anak jalanan yang cerdas membaca situasi, peka kapan menghindar sebelum ada razia, paham waktu terbaik mencari rezeki, dan bertahan hidup tanpa pernah membaca buku ekonomi. Atau anak yang katanya “bego geografi” di sekolah, tapi kalau main game, hafal peta dunia fantasy, tahu titik koordinat lokasi loot terbaik, dan bisa menghitung strategi perang lebih cepat dari guru matematikanya.
Dengan apa terasah itu semua kalau bukan karena skill membaca?
Literasi Sialan
Tapi betapa sial nasib mereka kalau kemudian berurusan dengan orang-orang pintar berhati mulia yang berkampanye literasi membawa tumpukan buku-buku menggunung tinggi. Buku-buku dibagikan, lalu dalam hitungan ke tiga, yak … mari kita baca bersama-sama!
Maka, beginilah adegannya (terinspirasi kejadian nyata).
Ada yang langsung membolak-balik halamannya seolah sudah terbiasa, padahal matanya hanya lompat-lompat tanpa benar-benar membaca. Ada yang diam di pojok, sesekali melirik buku di tangannya dengan canggung, seperti ragu tapi ingin mencoba.
Sebagian lagi berlagak santai, sok akrab dengan “jendela dunia”, berbicara tentang buku yang belum pernah mereka baca, mencoba terlihat paham agar tak dianggap tertinggal. Jelas terlihat mereka takut dianggap bodoh ketika dihadapkan pada bacaan yang menunggu untuk dimengerti, entah dengan percaya diri, malu-malu, atau diam-diam bertanya-tanya, kapan bel bubar akan berbunyi. Sementara itu, beberapa anak lain malah cekikik-cekikik tertahan, menyembunyikan rasa asingnya di balik candaan.
“Aku malas membaca,” bisik salah satunya, lalu tertawa.
Tapi orang-orang pintar mestinya paham, gak mungkin ada manusia malas membaca. Mereka cuma baca yang mereka suka dan mereka baca buuanyak! []